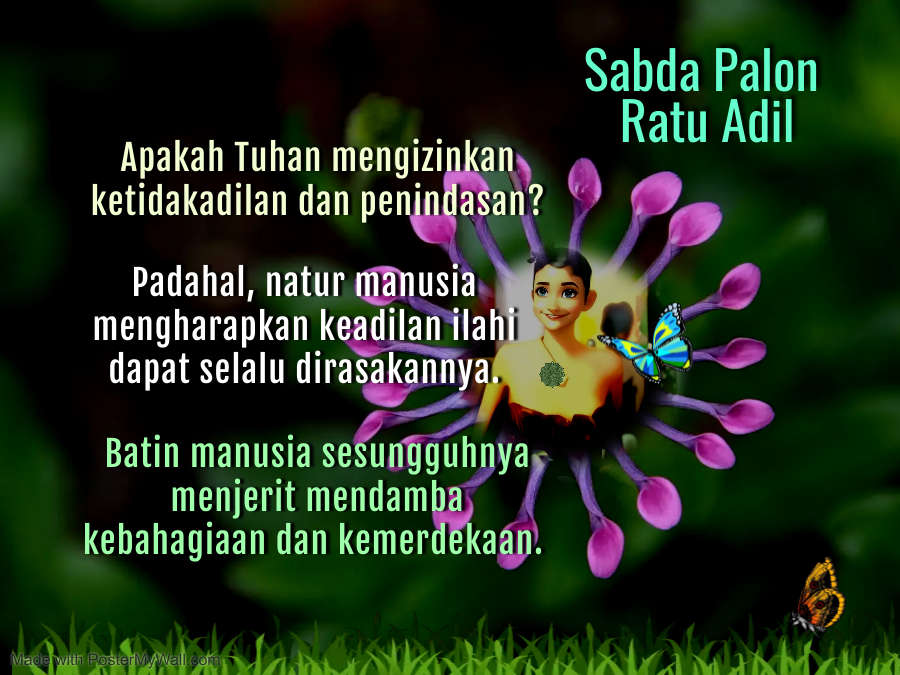Saya terinspirasi untuk menulis topik ini setelah menyaksikan obrolan Gita Wiryawan (di kanal Youtubenya) baru-baru ini dengan Fransiskus Assisi Suhariyanto (pengasuh kanal Asisi). Tanyanya, “Bagaimana Nusantara dapat meraih kejayaannya lagi?”
***
Saya akan memulai tulisan ini dengan pendapat Margaret Mead, seorang antropolog terkenal, mengenai awal mula peradaban manusia. Menurutnya, peradaban bukanlah dimulai dengan ditemukannya api, atau dihasilkannya teknologi dari batu sehingga melahirkan bangunan megalitik. Namun, peradaban dimulai dari evolusi homo sapien menjadi spesies yang saling merawat satu sama lain.
Salah satu dari “tujuh puluh wajah” pada Kisah Taman Eden maupun pada Kisah Abel-Kain adalah evolusi spesies manusia menjadi makhluk ber-nakhwa. Saya menemukan istilah “nakhwa” ini tidak sengaja saat membaca postingan sahabat saya mengenai salah satu khotbah Khaled Abu Al-Fadl.
Di dalam khotbah tersebut, Khaled Abu Al-Fadl mendefinisikan “nakhwa” sebagai rasa mulia dan bangga dalam membela hak-hak orang lain mendahului membela hak-hak diri sendiri.
Maka, di sini, secara nafsiologi, makhluk ber-nakhwa berarti makhluk yang menciptakan atau menghadirkan dirinya, yang mempraktekkan, dan yang selalu mengembangkan dirinya, sebagai sistem penopang bagi sesamanya.
Mula-mula di dalam Kisah Taman Eden itu terlihat pada kegelisahan Adam sebagai simbol manusia secara umum dan simbol spesies yang telah menemukan peradaban seperti dikatakan Margaret Mead itu.
Adam tidak menemukan sistem penopang kecuali pada Hawa yang biasa diartikan sebagai ibu dari segala yang hidup. Mengingatkan kita pada zikir Hu, Sang Maha Hidup, dan kata “Haya” adalah hidup. Hawa adalah simbol para shaman/wali yang mengelola sistem penopang mereka, sehingga disebut “penolong yang sepadan” (ezer kenojdow) dalam Taurat.
Kemudian, Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk mengkonsumsi Pohon Hadaat, simbol hasrat manusia untuk memfokuskan hidupnya kepada mengejar pengetahuan, sehingga hidupnya diarahkan kepada memenangkan pengetahuan baik-buruk, memberi makan egonya untuk segala hal, seperti kebenaran, spiritualitas, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan.
Di sisi lain, Tuhan membebaskan mereka menikmati dari Pohon Hayat, yaitu simbol hasrat manusia untuk selalu hidup, menghidupi, dan menghidupkan dunia. Agak berbeda dengan berbagai mitologi lain, Pohon Hayat di dalam Kisah Taman Eden ini juga adalah Pohon Keabadian, yang memberikan nafas kepada ruh manusia sehingga kekal abadi.
Dengan kata lain, Pohon Hayat adalah juga simbol sumber bagi manusia agar terus dapat menjadi makhluk ber-nakhwa. Si Ular Tua sebagai simbol dunia yang berlimpah kesuburan, keindahan, dan kesejahteraan itu menjadi tantangan agung bagi manusia untuk setia hanya mengkonsumsi dari Pohon Hayat, dan bukan dari Pohon Hadaat.
Si Ular Tua dalam gambaran masa modern adalah negara-negara yang serba maju, kehidupan yang serba mewah, kenyamanan hidup di dalam bangunan pencakar langit, menara-menara yang megah, teknologi yang luar biasa canggih, dan seterusnya.
Selanjutnya, dalam Kisah Abel-Kain, kita diberitahu mengenai sumber kejatuhan peradaban manusia. Tuhan bertanya kepada Kain, “Di mana Abel?” Kain menjawab, “Memangnya aku adalah mbok embannya Abel?” Bumi yang bersimbah darah Abel, menjerit kepada Tuhan dengan murka, sebagai simbol ruh “sistem penopang di alam kemanusiaan” yang menuntut pemulihan keadilan ilahi.
Kisah Abel-Kain ditutup dengan tiga petunjuk yang sangat menarik, mengenai kosmologi Al-Islam adalah dauran (cyclical) sebagai berikut.
Pertama, Abel adalah kelompok manusia yang tidak memiliki mekanisme pertahanan diri, yaitu yang tidak memiliki nakhwa dengan menerima sistem yang menindas, akan segera punah atau lebur ke dalam kelompok yang mensabotase dan menaklukkan mereka.
Iman Abel dijelaskan kembali antara lain dalam Kisah Ayub. Elihu menghadirkan koan kepada kita dalam argumentasinya bahwa manusia itu tidaklah seharusnya mengeluh kepada Tuhan melainkan menerima ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami untuk bersabar.
Koannya adalah argumentasi itu berimplikasi “Tuhan mengizinkan ketidakadilan dan penindasan”. Padahal, natur manusia mengharapkan keadilan ilahi dapat selalu dirasakannya. Batin manusia sesungguhnya menjerit mendamba kebahagiaan dan kemerdekaan. Nabi Ayub menggugah kita dengan koan itu, memaknai kesabaran bukanlah kehilangan nakhwa, dan tetap bersikap jujur kepada Tuhan bagaimana untuk menghadapi penindasan dan ketidakadilan.
Kedua, Kain adalah kelompok manusia yang menindas dan despotik. Mereka tidaklah memiliki nakhwa, tapi sukses karena semangat mereka berasal dari mengkonsumsi buah-buahan Pohon Hadaat. Sebab, Iman Kain adalah percaya melenyapkan manusia lain untuk dunia yang lebih baik. Inilah pengetahuan baik-buruk menurutnya yang paling benar dan terbaik. Ambisi inilah yang mendorong daya hidupnya.
Walau demikian, kelompok berarketipe Kain hanyalah memiliki masa tujuh generasi. Entah itu tujuh puluh tahun atau tujuh ratus tahun atau tujuh raja-raja, dan seterusnya.
Ketiga, sebagai pengganti Abel, Tuhan menghadirkan Seth bagi Adam dan Hawa. Inilah kelompok manusia yang memiliki nakhwa. Iman Seth adalah iman berdoa untuk menghadapi penindasan dan ketidakadilan, berupaya memulihkan keadilan ilahi.
***
Ada satu hal yang saya setujui dari khotbah Khaled Abu Al-Fadl mengenai nakhwa, yang akan saya adopsi dalam tulisan saya di sini perihal kejayaan Nusantara.
Secara intuitif, sebagai sarjana sejarah, saya melihat bahwa ribuan tahun sebelum tarekat Al-Islam didirikan dan atau dimapankan oleh Nabi Idris (Enokh atau Khidr) pada 3760 SM di seluas peradaban Mesopotamia, mereka yang diceritakan di dalam Kisah Taman Eden dan Kisah Abel-Kain adalah para imigran dari Nusantara ketika terjadi perubahan iklim dahsyat. Perubahan in dikenal sebagai Era Driyas Muda, sekitar 12,000-13,000 tahun lalu.
Pengalaman berhijrah mereka melalui banjir besar dan atau naiknya level air laut dan tenggelamnya banyak daratan itu direproduksi dalam Kisah Bahtera Nuh untuk merenungi dan menghayati pengalaman yang kedua kalinya dalam menghadapi perubahan iklim. Banjir itu berlangsung di Mesopotamia, ketika di daratan Arabia terjadi penggurunan, dan di seluas Sumeria terjadi kerusakan alam akibat eksploitasi dengan pertanian yang serakah dan massif.
Sebelum peradaban Sumeria jatuh dan kini kita hanya dapat melihat sisa-sisa peninggalannya saja, Nabi Idris telah menemukan kembali “kearifan dari Nusantara” para leluhurnya, mengklaim sebagai penerus Nabi Seth, “menciptakan agama baru” yang berakidahkan tauhid dan keadilan ilahi, yang berarti meliputi tauhid adalah satu kemanusiaan. Imannya adalah Iman Seth. Iman yang ber-nakhwa itu.
Kata-kata “tauhid adalah satu kemanusiaan” berasal dari sabda Imam Ali Murtaza ibn Abi Talib, “Sesungguhnya kita semua bersaudara dalam satu kemanusiaan.”
***
Mengadopsi pandangan Khaled Abu Al-Fadl mengenai “Arab memperoleh Islam saat itu karena nakhwa yang mereka miliki”, maka kalau kita memerhatikan dengan seksama di dalam Alkitab-Alquran, kita akan temukan bahwa menang karena kenakhwaan seseorang/sekelompok orang sehingga mereka dapat memperoleh buah-buahan bergizi dari Pohon Hayat. Itulah yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia.
Baik itu kita memaknai Islam sebagai gerakan sosial yang dipelopori Nabi Muhammad pada abad ketujuh Masehi, maupun Islam sebagai gerakan sosial dari tarekat Al-Islam yang selalu dihidupkan atau dibangkitkan kembali oleh para nabi dan rasul dari garis silsilah parampara Nabi Idris.
Bahkan juga Islam sebagai karakter kejiwaan bagi seluruh gerakan sosial dari berbagai Pohon Hayat di peradaban selain Mesopotamia. Misalnya, Buddhisme, Shivais Kashmiri, Advaita, Sikhisme, Taoisme, Konfucianisme, Mohisme, dan lain-lain.
Sekali lagi, saya setuju bahwa karena kenakhwaan itulah seseorang/sekelompok orang memperoleh buah-buahan bergizi dari Pohon Hayat. Dan, itulah yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia.
Kita ingat bahwa dalam Kisah Taman Eden, setelah Adam dan Hawa mengkonsumsi dari Pohon Hadaat, mereka terlempar dari Eden, simbol dunia yang dibentengi nafs-Nya, terlindung dari kematian dan kerusakan. Kemudian, Pohon Hayat pun dilindungi dengan pedang api bernyala, simbol kesukaran untuk memperoleh buah-buahan Pohon Hayat.
Mari kita lihat beberapa parampara yang merupakan mata rantai silsilah parampara Nabi Enokh.
Yang dilakukan Nabi Nuh adalah dengan rasa bangga dan mulia bersemangat membela hak-hak manusia dan makhluk kendati dihujat di sana-sini dengan membangun bahtera. Bahtera Nuh adalah simbol sistem berkehidupan yang dibangun bersifat sebagai sistem penopang, yang dalam bahasa kekinian bersifat berkelanjutan.
Begitu pun Nabi Ibrahim dengan nakhwanya membela hak-hak manusia lain, dengan mengangkat senjata (membebaskan Nabi Luth). Lalu, melakukan ikonoklasme, yang secara gegabah dipahami sebagai intoleransi terhadap keberagamaan umat lain.
Ikonoklasme yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah menghancurkan konsep-konsep, nilai-nilai, dan model-model yang dijadikan adidaya saat itu untuk menindas dan melakukan ketidakadilan. Karena itulah disebut berhala, dan penganutnya disebut musyrik (pagan).
Apa yang sesungguhnya membuat Nabi Ibrahim menjadi bapak bagi bangsa-bangsa?
Nabiah Miryam, Nabi Musa, dan Nabi Harun telah membangkitkan nakhwa dalam diri Bani Israel, yaitu sekelompok manusia yang menerima dan mengakui para otoritas Transmisi dari Pohon Hayat Nabi Enokh. Mereka melawan Firaun, simbol pelaku sistem yang menindas dan tidak adil, meski tampak membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi dunia.
Dengan nakhwa itulah, ribuan Bani Israel menerima wahyu di Sinai, dan menjadi “putra-putra Tuhan”. Sejak itulah yang disebut Bani Israel adalah siapapun yang menerima, mengakui, dan menjalani Wahyu di Sinai itu. Yang disebut Alfurqan di dalam Alquran.
Jadi, Bani Israel bukanlah penganut Yudaisme, bukan suku bangsa (tribe), dan bukan pula bangsa (nation-state) maupun umat keagamaan tertentu. Bani Israel adalah siapa pun dari silsilah barokah Nabi Idris/Enokh yang menempuh lelaku Dekalog/Alfurqan.
Nabi Daud menjadi nabi dan raja, juga karena nakhwanya. Begitu pula nabi dan raja Sulaiman kemudian berhak menjadi parampara berikutnya. Pada saat itu, mereka memerintah kerajaan yang tidak lebih luas daripada kotamadya Jakarta Pusat di dalam kepungan adidaya-adidaya. Tetapi, mereka teguh tidak menjadi imperialis-konsensus yang Manifest Destiny seperti adidaya-adidaya tetangga mereka.
Hal penting lain adalah Khaled Abu Al-Fadl mengatakan, sayangnya nakhwa mudah takluk ke dalam penindasan dan despotisme.
Menurut saya, hal itu terjadi ketika kenakhwaan suatu kelompok dan atau seseorang tidak dijalani secara shamanis, yaitu, memelihara diri dengan Pohon Hayat. Untuk memelihara kenakhwaan kita mesti menerima dan mengakui otoritas Pohon Hayat, pengasuhan Pohon Hayat, dan pembimbingan Pohon Hayat. Bahasa lainnya adalah “leluhur” — yang luhur, yang sidha. Ini sebabnya dalam bahasa kita, “tree” adalah pohon, yang melahirkan kata memohon.
Pudarnya nakhwa itulah yang terjadi kepada bangsa Yehuda dan Israel Utara, meski para nabi dan rasul hadir sebagai Pohon Hayat yang nyata terlihat (visible) di hadapan mereka. Namun, mereka enggan menerima pengasuhan Pohon Hayat yang hadir di tengah-tengah mereka. Sampai akhirnya mereka dijajah Neo-Asyur, Neo-Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi.
***
Jika Nabi Ibrahim adalah orang Ur-Asyur, dan Nabi Musa adalah orang Mesir, maka Nabi Daniel dan Nabi Ezra (Uzair) adalah orang Persia, sedangkan Makabe adalah orang-orang Yunani. Kemudian, Nabiah Maria, Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis serta Yesus Kristus atau Nabi Isa Almasih adalah orang Romawi. Di sini, yang saya sebut itu berdasarkan “negara” tempat mereka tinggal (entah atas dasar penguasanya atau bahasanya atau toponimnya), seperti kita menyebut Arab dan Nusantara.
Setelah mengatakan “Islam berada di tangan Arab yang saat itu memiliki nakhwa”, Khaled Abu Al-Fadl mengatakan kejatuhan Islam adalah ketika mereka takluk kepada penindasan dan despotisme, dan menanggalkan kenakhwaan mereka. Yang saya lihat, kenakhwaan itu bergelora sejak setidak-tidaknya pada diri Qusai, atau pada diri Hashem (Hushim). Dan, puncaknya adalah pada Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra, dan Imam Ali Murtaza.
Mereka mengklaim Maad ibn Adnan (murid dan abdal Nabi Yeremiyah) untuk menyalakan nakhwa pada diri mereka, di negeri mereka sebagai orang Arab. Sementara saudara-saudara Yahudi dan Kristen mereka takluk di dalam imperialisme Romawi dan Persia.
Pada abad ketujuh Masehi, gerakan sosial mereka berani melawan Quraish, konfederasi yang merupakan simbol oligarki saat itu, kumpulan oportunis yang kadang-kadang menjadi antek kolonial Romawi, dan kadang-kadang menjadi antek kolonial Persia.
Namun, begitu mereka mengabaikan Pohon Hayat, perlahan demi perlahan mereka terseret jatuh ke dalam penindasan dan despotisme dengan dibunuhnya Imam Ali Murtaza: faksi Umayyah berhasil menguasai gerakan Islam dan bahkan menciptakan agama imperialis-konsensus darinya — di tangan Abdul Malik dan Yusuf Al-Hajjaj.
Demikianlah nasib mereka yang tidak belajar dari sejarah. Belajar sejarah saja tidaklah cukup. Tetapi, belajar dari sejarah, itu jauh lebih penting. Padahal, sebelumnya itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus Kristus.
Gerakan sosial Islam yang telah berhasil dibangkitkan Yesus Kristus pada abad pertama Masehi dipercayakan di tangannya dan para muridnya karena kenakhwaan mereka.
Ajaran dan kearifan Al-Islam yang disampaikan Yesus Kristus menjadi semakin populer selama abad kedua Masehi sampai masa Wabah Antonia banyak yang menerima dan mengakui otoritas Beliau karena para mursyid, murid, dan abdal Sang Mesias bernakhwa.
Konsep jihad dan mati syahid sebagai kemuliaan dipopulerkan mula-mula oleh para mursyid, murid, dan abdal Sang Mesias dalam semangat kenakhwaan mereka. Ini bukan perjuangan untuk memberi makan ego spiritual pribadi maupun golongan seperti yang dipahami arus utama Kristen saat ini.
Jadi, para mursyid, murid, dan abdal Sang Nabi SAW hanyalah mewarisinya dan melanjutkannya sebagai suksesor Sang Mesias dan ahlulbaitnya (baca: mursyid, murid, dan abdal Pohon Hayat).
Tetapi, begitu para mursyid, murid, dan abdal Sang Mesias itu memilih berkonsensus dan mengabaikan Pohon Hayat, akhirnya Kekaisaran Romawi sukseslah mencaplok Kekristenan ke dalam penindasan dan despotismenya.
Bagaimana pun juga, Kekristenan setelah konsili-konsili jatuh ke tangan imperialisme adalah “agama-agama misteri Hellenis yang mengadopsi Sang Mesias, Yudaisme, dan Alkitab ke dalam struktur, sistem, dan dogma mereka.”
Kehadiran kembali gerakan sosial Islam pada abad keenam dan ketujuh Masehi sesungguhnya “dimaksudkan Tuhan” untuk menghadapi penindasan dan ketidakadilan dari Kekristenan imperialis-konsensus tersebut, walau akhirnya disabotase oleh Umayyah pada awal abad kedelapan Masehi.
Namun, penting pula diingat, bahwa Revolusi Abbasiyah berhasil karena membangkitkan kenakhwaan itu di antara Non-Arab yang ditindas dan didiskriminasi selama masa penjajahan Umayyah. Meski, lagi-lagi, kembali jatuh ke dalam imperialis Abbasiyah.
***
Kitab TBAI menyiratkan kosmologi yang dianut Al-Islam adalah dauran, dan sejak 3760 SM itu, sejak 1 Anno Mundi, itulah awal mula daur generasi Nabi Idris, yang lamanya kira-kira tujuh ribu tahun (solar maupun lunar).
Ketika Gita Wiryawan menyebut suatu titik penting dalam abad-abad kemanusiaan daur Nabi Idris ini, yaitu abad ke-13 M, maka ini menjadi titik renungan penting mengenai al-nakhwa ketika membahas kejayaan Nusantara.
Kemenangan Ottoman (yaitu orang-orang Turk Oghuz) ke atas Islam pada abad ke-16 M adalah penggenapan nubuatan Yesus Kristus kepada musahipnya Yohanes Patmos.
Sekitar tiga abad setelah kerajaan Ottoman berdiri, Mongol menaklukkan Abbasiyah, merosotnya Majapahit dan Yuan serta Buddhisme imperialis-konsensus, dan hadirnya Sayyid Bektash Wali yang diyakini oleh para muhibnya sebagai reinkarnasi Imam Ali Murtaza.
Di benua Amerika, seakan-akan melalui abad-abad kejayaan terakhir sebelum Eropa menjajah mereka, sementara berbagai kerajaan Islam yang cukup besar mulai muncul di India, Afrika, dan Nusantara (Samudra Pasai).
Orang-orang Mongol dan Turk itu tampaknya memiliki semangat nakhwa, sehingga Islam jatuh ke tangan mereka — menjadi Rum Seljuk (Turk), Mughal (Mongol), Ottoman (Turk), dan lain-lain Dan, mungkin juga orang-orang Melayu di Pasai itu, serta sebagian Persia yang melahirkan Safawiyah pada abad ke-16 M.
Namun, begitu semangat itu tidak dibarengi dengan bersampradaya-parampara kepada Pohon Hayat, sebagian dari mereka menjadi adidaya yang menindas dan despotik. Yang lainnya menjadi seperti Abel, menerima penindasan dan ketidakadilan sebagai diizinkan Tuhan.
Tampaknya, dari obrolan Gita Wiryawan dengan FA Suhariyanto, memandang merosotnya peradaban Nusantara sejak abad ke-13. Pertanyaan pentingnya, apakah kejayaan yang dimaksud Gita Wiryawan? Gita menyebut kejayaan secara budaya, secara intelektual. Yang juga terserlah pada berbagai arsitektur yang mengagumkan.
Tentu saja, saya keberatan dengan pengertian kejayaan yang bersifat jasmaniah, bukan bersifat kebudayaan adiluhur, yang memancarkan satu kemanusiaan atau humanisme imparsial. Saya juga keberatan jika kekalahan atau kemerosotan hanyalah yang bersifat jasmaniah seperti tiadanya bangunan-bangunan megah seperti di dalam kompleks masyarakat adat Lebak Kanekes.
Jika kita ingin mengembalikan kejayaan Nusantara, kita perlu bertanya, adakah kita masih bernakhwa. Bahasa kita menunjukkan hal ini. Hanya sedikit bahasa yang memiliki perbedaan antara “kita” dan “kami”. “Kita membela hak-hak mereka, dan kami membela hak-hak kalian.”
Kita perlu tetap memelihara gotong-royong yang merupakan salah satu wujud sistem penopang yang khas nakhwa itu. Kita perlu memelihara budaya komunal yang guyub, alih-alih tergerus dalam tren individualisme dan egoisme khas kapitalisme saat ini.
Yang perlu bangkitkan mula-mula sekali bukanlah pencapaian sains dan teknologi maupun ekonomi untuk menyaingi negara-negara maju. Tetapi, menguatkan kembali rasa bangga dan rasa mulia untuk membela hak-hak kehidupan mendahului hak diri sendiri, di dalam setiap sistem kehidupan kita, seperti sistem ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Dalam ungkapan Jawa, “Urip iku urup”, inila suatu nakhwa khas Jawa.
Baru kemudian, ketika kenakhwaan itu bergelora, kita memiliki fondasi yang kokoh dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahun untuk menginovasi dan mengembangkan sistem-sistem penopang itu.
Keberhasilan para pejuang pendiri NKRI pada 1945-1949 justru karena kenakhwaan mereka. Mereka merasa bangga dan mulia jika harus berjuang sampai mati untuk dapat membebaskan negeri ini dari cengkraman penjajah agar tetangga, saudara, dan sahabat mereka tidak lagi menderita di bawah belenggu penjajah.
Di samping tidak lagi bersampradaya seperti para leluhur, ada satu masalah lagi. Seperti yang dikatakan Gita Wiryawan bahwa sifat dasar orang-orang di Asia Tenggara lebih menyukai perdamaian daripada perang. Maka, ini juga menjadi masalah lainnya.
Apabila terlalu pasrah dan terlalu gentar sehingga tidak mau membela hak-hak orang lain yang dirampas, akhirnya kita mengalami hal-hal seperti pada masa Orde Baru, dan kolonialisme Eropa pun sukses karena kita enggan berkonflik dengan saudara kita yang menjadi antek Kompeni dan pemerintah Hindia-Belanda.
Antek-antek itu, adalah mereka yang tidak bersampradaya kepada Pohon Hayat (apapun) dan lebih memilih berdamai dengan penjajah demi keuntungan pribadi dan keluarganya. Inilah yang masih terus terjadi di Indonesia sampai sekarang.
Seperti yang dialami para muhib Al-Islam sejak masa jatuhnya Israel Utara dan Yehuda ke tangan Neo-Asyur dan Neo-Babilonia, mereka yang memilih memberi makan ego mereka daripada bersampradaya-parampara, lambat-laun kenakhwaan mereka memudar, dan akhirnya mengalami penjajahan.
Karena, penjajah telah memilih mengaplikasikan kekuasaan Tuhan pada diri mereka untuk memenangkan pengetahuan baik-buruk di dunia, dan “hukum alam” memberi kesempatan kepada mereka selama tujuh generasi untuk bertaubat, atau terus berbuat zalim untuk lenyap selama-lamanya.
Takdir kita tampaknya bergerak di dalam pola yang kita pilih, apakah menjadi Abel, Kain, atau Seth. Sebagian orang dari negara yang dikatakan maju itu telah berupaya untuk bertaubat dengan kenakhwaan yang bertumbuh dalam diri mereka, meski pada masa yang sama mereka harus melawan raksasa-raksasa di antara mereka sendiri yang sangat Kain.
Kejayaan yang terserlah secara spiritual dan intelektual, di dalam kebudayaan kita, yang tidak hanya mimikri (seperti yang dikeluhkan Gita Wiryawan mengenai kecendrungan kita menggemari dan mengimitasi kebudayaan asing mentah-mentah, tidak seperti pada masa lalu). Adakah ini mungkin dicapai tanpa memohon bimbingan dari Pohon Hayat, tanpa menerima pengasuhan dari Pohon Hayat, dan tanpa memiliki jati diri?
Seseorang tidaklah mungkin memiliki jati diri tanpa memiliki empati dan nakhwa, karena ia membentuk dan mengasah dirinya sedemikian rupa untuk menjadi sistem penopang bagi kehidupan. Sistem penopang selalu membutuhkan karakter yang kuat, tangguh dan bersedia dhirti (fortitude). Dan, semua ini adalah keterampilan yang harus selalu dilatih. Begitu juga halnya suatu kelompok manusia.
Seperti halnya kejayaan seorang manusia sejatinya menjadi manusia seutuhnya. Begitu pun kejayaan suatu bangsa. Sejatinya jelaslah berarti kejayaan menjadi bangsa yang Manusia, yang memanusiakan sesama, dan menghadirkan kemanusiaannya di alam kehidupan seluas-luasnya.
Namun, dengan riuh rendah politik identitas, ujaran kebencian dan pemlintiran kebencian, perampasan tanah masyarakat adat dan hak hidup mereka, kemiskinan struktural di mana-mana, sistem kesehatan yang masih belum sepenuhnya “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, dan sebagainya… Adakah tanpa humanisme imparsial melalui berbagai gerakan nakhwa, bangsa Indonesia akan mencapai kejayaan seperti yang didambakan banyak orang?
Sidhamastu,
Grandsheikha Hefzibah Gayatri Wedotami Muthari.
========